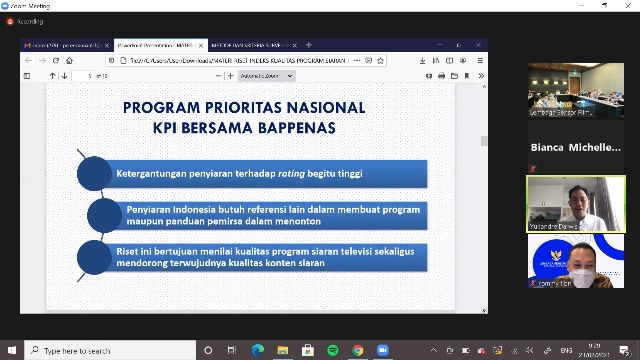- Detail
- Ditulis oleh RG
- Dilihat: 25721

Jakarta – Gelombang desakan serta dukungan agar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektornik (UU ITE) segera direvisi datang dari berbagai kalangan. Berbagai kegaduhan yang timbul akibat dari adanya pasal karet dalam UU ini menjadi alasannya. Padahal UU yang dilahirkan pada 2008 ini diniatkan bukan untuk mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui internet.
Terkait wacana revisi UU tersebut, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat), Hardly Stefano, ikut mendukung rencana tersebut. Menurut dia, perubahan isi UU ITE khususnya pada pasal karet yang menjadi polemik di masyarakat harus dilakukan. Upaya ini dapat memberi ruang yang lebih dinamis pada kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa dibayangi adanya ancaman hukum pidana.
“Memang ada yang berpandangan bahwa UU ITE ini diperlukan untuk mencegah dampak negatif dari dinamika komunikasi di internet. Namun tak sedikit pula yang berpandangan bahwa UU ITE ini merupakan UU karet yang berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat,” ujar Hardly dalam Webinar yang diselenggarakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (FDK UINSA) dengan tema “Kebebasan Berpendapat dan Wacana Revisi Pasal Karet UU ITE”, Senin (1/3/2021).
Jika UU ini direvisi, lanjut Hardly, pendekatan hukumnya sebaiknya berkaca pada UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No.40 tahun 1999 tentang Pers. Menurutnya, kedua UU ini meskipun mengatur tentang kebebasan dan tanggungjawab berekspresi dan berpendapat dalam media mainstream (konvensional) tetapi mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif dengan tetap melakukan tindakan imperatif.
“Pelanggaran terhadap norma dalam UU Pers dilakukan melalui mekanisme verifikasi, mediasi dan penyampaian klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka. Sedangkan pelanggaran pada norma UU Penyiaran, selain dilakukan verifikasi dan mediasi, juga dikenakan sanksi administrasi. Sanksi pidana menjadi pilihan terakhir untuk dikenakan. Pola seperti ini dapat diterapkan dalam penanganan kasus pelanggaran UU ITE. Jadi lebih persuasi dan edukatif. Lantas, sebaiknya pola yang mengedepankan pendekatan represif dihilangkan dalam paradigma UU ITE hasil revisi nanti,” usul Hardly.
Kapolri memang sudah mengeluarkan Surat Edaran No.2 tahun 2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif pada 19 Februari lalu. Intinya surat tersebut memerintahkan seluruh penyidik kepolisian mengedepankan restoactive justice dalam penegakan UU ITE.
“Keluarnya surat edaran dari Kapolri terkait penegakan UU ITE ini, kita anggap sebagai terobosan hukum, namun sekaligus menunjukkan bahwa memang ada yang kurang tepat dalam paradigma penegakan hukum UU tersebut. Dengan ancaman hukuman pidana, terlihat bahwa paradigma UU ITE lebih mengedepankan prinsip represif-imperatif. Surat edaran ini telah memberi nuansa restoactive, dengan mengedepankan persuasi dan edukasi, serta langkah preemtif dan preventif,” tutur Hardly.
Meskipun telah ada terobosan hukum, Hardly mengatakan surat edaran ini masih menjadi instrumen hukum yang lemah dibandingkan UU. Menurutnya, surat edaran adalah instrumen pengaturan internal dan pada akhinya harus tunduk pada UU sebagai landasan hukum positif yang legitimated.
“Dapat dikatakan, SE Kapolri ini merupakan solusi sementara. Dibutuhkan solusi yang lebih sistematis dan komprehensif, salah satu opsinya adalah kembali melakukan revisi atas UU ITE atau membuat UU khusus tentang konten internet. Revisi maupun pembuatan UU baru terkait dinamika internet harus mampu mengatur titik keseimbangan antara kebebasan berekspresi di satu sisi dengan kemanfaatan berekspresi di sisi yang lain. Antara kebebasan berpendapat dengan tanggung jawab berpendapat. Juga mengatur titik kompromi antara kebebasan individu dengan norma sosial dan peraturan hukum yang berlaku,” jelas Komisioner bidang Kelembagaan KPI Pusat ini.
Hardly juga mengusulkan, untuk menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat, dibutuhkan semacam lembaga pengawasan dan abitrase konten atau informasi elektronik. Menurut dia, lembaga ini sebaiknya merupakan representasi perwakilan masyarakat atau civil society seperti Dewan Pers dan KPI. Bukan lembaga struktural pemerintahan.
“Keberadaan lembaga pengawasan dan abitrase konten internet ini dapat dengan membentuk lembaga baru. Namun jauh lebih baik jika dapat mengoptimalkan lembaga negara independen yang telah ada dengan memberikan perluasan kewenangan,” tandas Hardly Stefano.
Dalam webinar tersebut, turut hadir narasumber lain yakni Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, dan CEO sekaligus Editor Chief Telegraf.co.id danTelegraf.id, Koeshondo W. Widjojo. ***